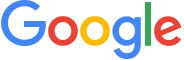Implementasi Asuransi Petani di Indonesia
Menjadikan Indonesia kembali menjadi Negara agraris yang berdaulat pangan sepertinya kembali menjadi cita-cita pemerintah.
Hal itu terbukti dengan dikeluarkannya program asuransi pertanian sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani pasal 37 ayat (1) yang berbunyi “Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melindungi usaha tani yang dilakukan oleh petani dalam bentuk asuransi pertanian”.
Secara lebih rinci, program asuransi pertanian diatur melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian dimana peraturan tersebut membahas hal teknis program tersebut.
Pemerintah telah menjelaskan bahwa program tersebut akan memberikan penggantian sebesar Rp6 juta per hektar dengan premi sebesar Rp180 ribu dimana pemerintah akan memberikan subsidi sebesar 80% sehingga para peserta hanya perlu membayar sebesar Rp36 ribu.
Asuransi pertanian tersebut masih memiliki beberapa hal yang perlu untuk dievaluasi kembali. Pertama dari segi ganti rugi, yang disebutkan sebesar Rp6 juta per hektar.
Jika dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan petani, maka angka tersebut kurang mencukupi. Ongkos usaha tanaman tahun 2014 untuk padi sawah adalah sebesar Rp12,7 juta sedangkan untuk padi ladang adalah sebesar Rp7,8 juta.
Padahal petani juga bukan hanya perlu modal untuk bisa kembali bercocok tanam, tetapi juga membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya sendiri serta rumah tangganya sampai masa panen berikutnya.
Angka tersebut tentu saja akan berbeda di setiap daerah dan kemungkinan besar relatif lebih mahal di luar Jawa yang notabene memiliki infrastruktur yang kurang memadai, harga input yang tinggi dan pasokannya terbatas.
Angka ganti rugi yang rendah akan mengurangi minat para petani untuk berpartisipasi dalam program ini, kendati biaya premi yang rendah karena disubsidi oleh pemerintah.
Seandainya pemerintah berniat menaikkan besaran ganti rugi pun, maka pemerintah masih perlu mengkaji ulang apakah menutupinya dengan cara menaikkan premi yang tentu akan memberatkan petani atau meningkatkan anggaran subsidi premi yang akan berdampak terhadap APBN.
Hal ini semakin diperparah dengan pengetahuan masyarakat Indonesia terhadap asuransi masih rendah. Jangankan masyarakat petani yang mayoritas berada di pedesaan, penduduk perkotaan yang memiliki akses lebih terhadap instrumen keuangan masih sangat meragukan asuransi.
Selain itu, asuransi pertanian hanya memberikan perlindungan terhadap risiko gagal panen, padahal petani Indonesia memiliki risiko lain seperti harga jual yang rendah dan harga input seperti pupuk dan benih yang terlalu tinggi dan sulit dicari.
Kedua, permasalahan berikutnya adalah untuk saat ini pemerintah hanya mengakomodir petani padi sebagai salah satu upaya mewujudkan swasembada petani.
Hal ini bisa dibilang wajar dan tepat karena program ini baru dimulai dan membutuhkan waktu bagi pemerintah untuk bisa melakukan ekspansi agar bisa menampung asuransi untuk semua petani.
Dalam jangka panjang, diharapkan pemerintah mampu memberikan akses asuransi kepada semua petani di Indonesia tanpa terkecuali termasuk asuransi untuk subsektor dari pertanian seperti peternakan dan perikanan.
Ketiga, asuransi pertanian di Indonesia saat ini berbasis indemnity-based atau ganti rugi, dimana pemerintah akan melakukan penggantian berdasarkan kerugian atau kerusakan yang benar-benar terjadi dan dialami petani.
Sistem ini memiliki kelemahan terkait biaya yang tinggi yaitu biaya administrasi dan biaya lain-lain seperti biaya survey risiko dan biaya inspeksi untuk memastikan apakah kerugian benar-benar dialami oleh petani atau tidak.
Apalagi dengan struktur pertanian di Indonesia dimana rumah tangga tani di Indonesia mencapai 40.000.136 rumah tangga dengan luas lahan 8.581,19 m2 (kurang dari 1 hektar) sehingga membutuhkan waktu dan biaya yang besar bagi pihak asuransi untuk mendata sekaligus melakukan inspeksi.
Keempat, sistem indemnity based lebih rentan memicu terhadap terjadinya adverse selection dan moral hazard.
Adverse selection adalah situasi dimana mereka yang memilih untuk mengikuti asuransi pertanian adalah mereka yang memiliki risiko tinggi, lebih besar dibandingkan premi yang dibayarkan.
Moral hazard adalah situasi dimana peserta asuransi bertindak lebih berisiko karena merasa setiap kerugian akan diganti oleh pihak asuransi.
Moral hazard, dalam beberapa kasus seperti yang terjadi di India dapat berubah menjadi fraud atau kecurangan dimana masyarakat secara sengaja menggagalkan panennya untuk mendapatkan ganti rugi.
Hal ini terjadi karena biaya pengawasan yang tinggi bagi pihak asuransi untuk memastikan apakah kegagalan panen benar-benar terjadi karena faktor yang sudah tertera dalam kontrak atau merupakan unsur kelalaian atau bahkan kesengajaan dari pihak petani.
Beberapa hal bisa dilakukan pemerintah untuk lebih mengoptimalkan utilitas dari asuransi pertanian.
Pertama, asuransi pertanian sebaiknya menjadi sebuah program wajib yang harus diikuti oleh semua petani. Hal ini tentu saja bukan hal yang mudah terutama untuk meyakinkan mereka yang memiliki kepercayaan yang rendah terhadap sistem asuransi dan petani yang sebenarnya memiliki risiko gagal panen yang rendah.
Namun, asuransi pertanian, selain untuk pengaman bagi petani apabila terjadi gagal panen, asuransi pertanian juga sebagai pengenalan instrumen asuransi kepada petani.
Kebijakan untuk mewajibkan petani mengikuti asuransi pertanian sebaiknya diikuti dengan sosialisasi yang intensif terhadap petani sehingga memahami pentingnya asuransi dan mengerti teknis prosedurnya.
Selain itu, perlu pertimbangan yang matang terkait pengeluaran subsidi yang perlu dikeluarkan pemerintah untuk membiayai premi asuransi petani tersebut.
Selain itu, pertanian di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Mulai dari jenis sawah, pola waktu tanam, jenis tanaman, cuaca dan kondisi geografis, yang menyebabkan satu daerah dengan yang lain memiliki risiko yang berbeda.
Karena perlu kajian lebih mendalam dari pemerintah mengenai risiko, premi dan ganti rugi yang perlu dikenakan berdasarkan faktor-faktor tersebut yang seharusnya berbeda-beda.
Akan menjadi tidak adil apabila petani dengan risiko yang rendah perlu membayar premi yang sama dengan petani berisiko tinggi padahal jumlah ganti rugi yang diberikan sama.
Begitu pula apabila ganti rugi yang diberikan sama padahal biaya yang dikeluarkan petani berbeda karena perbedaan jenis tanaman.
Hal lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa petani memiliki risiko lain terkait dengan kepastian harga jual dan harga input serta ketersediannya di pasar.
Ini dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk memasukkan kriteria ini ke dalam kontrak asuransi atau menyusun program lain yang terintegrasi dengan asuransi pertanian.
Misalnya, pemerintah akan memberikan harga yang lebih murah serta akses ke faktor input semisal pupuk yang lebih baik kepada petani yang memiliki asuransi pertanian.
Strategi seperti ini diharapkan lebih persuasif untuk mengajak masyarakat berasuransi sekaligus memberikan kepastian keuntungan kepada petani yang berdampak terhadap terwujudnya ketahanan pangan yang sustainable sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.
Dengan berbagai tinjauan terhadap asuransi pertanian, penulis berpendapat bahwa program ini perlu untuk dilanjutkan bahkan ditingkatkan sebagai sebuah niat baik pemerintah untuk memakmurkan petani Indonesia.
Program ini perlu untuk terus diawasi dan dievaluasi secara berkelanjutan agar menjadi lebih efektif dan efisien.
Selain itu dalam jangka panjang, banyak manfaat yang bisa didapatkan dari program ini yakni menghindari semakin berkurangnya rumah tangga tani dan lahan pertanian dari tahun ke tahun serta meningkatkan daya beli petani Indonesia sehingga bisa menjadi profesi yang lebih diminati.